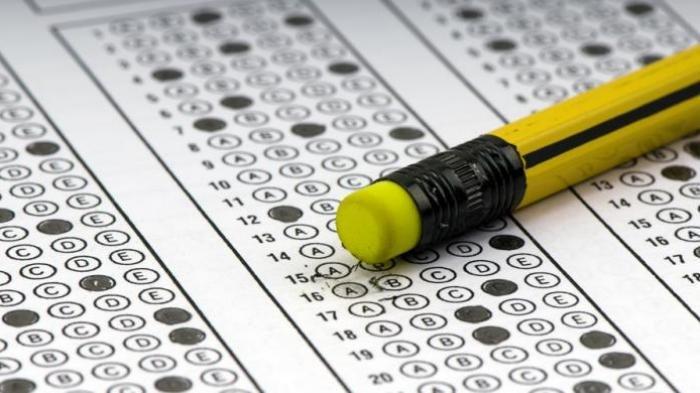Penghapusan Ujian Nasional (UN) di Indonesia sempat menjadi titik balik yang besar dalam sistem pendidikan. Setelah bertahun-tahun menjadi simbol puncak evaluasi siswa, UN akhirnya dihentikan dengan alasan ingin menciptakan sistem pendidikan yang lebih manusiawi, holistik, dan relevan. link resmi neymar88 Namun, meskipun bentuknya telah berubah, pertanyaan penting muncul: apakah sistem pendidikan kita benar-benar berubah, atau hanya mengganti wajah dari penilaian lama ke penilaian baru yang tak jauh berbeda?
Jika tujuan penghapusan UN adalah membebaskan siswa dan guru dari tekanan angka, maka realitas di lapangan menunjukkan bahwa tekanan itu tidak benar-benar hilang—hanya bergeser bentuk.
Dari UN ke Asesmen Nasional: Nama Boleh Ganti, Tekanan Tetap Ada
Kini, Ujian Nasional digantikan dengan Asesmen Nasional (AN) yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Pemerintah menyebut ini bukan penilaian individu, tapi evaluasi sistem. Namun di sekolah-sekolah, AKM kerap tetap dianggap sebagai tolok ukur “pencapaian”, meskipun secara teknis tidak menentukan kelulusan.
Akibatnya, sekolah masih berlomba-lomba menyiapkan siswa dengan latihan soal, try out, dan bimbingan belajar, mirip dengan era UN. Guru-guru pun kembali dihadapkan pada target nilai rata-rata sekolah, sementara siswa tetap merasa tegang karena hasil asesmen akan berdampak pada reputasi sekolah mereka. Ini memperlihatkan bahwa semangat perubahan belum sepenuhnya meresap ke dalam praktik pendidikan harian.
Budaya Angka yang Belum Usai
Kebiasaan menilai siswa melalui angka masih sangat kuat. Raport masih dipenuhi deretan nilai 0 sampai 100, dan peringkat kelas masih menjadi patokan keberhasilan. Siswa yang cerdas secara verbal, artistik, atau interpersonal kerap kali tidak mendapatkan tempat karena nilai akademik tetap menjadi raja.
Padahal, para ahli pendidikan telah lama menyuarakan bahwa kemampuan manusia terlalu kompleks untuk direduksi menjadi angka tunggal. Kecerdasan emosional, kemampuan kolaborasi, daya tahan mental, dan keingintahuan adalah komponen penting dalam dunia nyata, namun sering kali tidak dihargai dalam sistem penilaian formal.
Guru yang Terjebak Target, Bukan Proses
Guru adalah aktor penting dalam perubahan pendidikan. Namun ketika beban administrasi dan tekanan nilai masih mendominasi, maka guru sulit memberi perhatian penuh pada proses belajar yang mendalam. Banyak guru merasa harus “mengejar kurikulum”, menghabiskan waktu untuk evaluasi formal, dan memastikan siswa mencapai angka tertentu, ketimbang membimbing siswa untuk memahami makna pembelajaran.
Hal ini menciptakan situasi di mana pengajaran menjadi kegiatan untuk menyiapkan siswa menghadapi ujian, bukan untuk mengembangkan cara berpikir atau membangun karakter. Akibatnya, kelas menjadi tempat latihan hafalan, bukan ruang diskusi atau eksplorasi gagasan.
Siswa Terbentuk untuk Memuaskan Sistem
Ketika sistem pendidikan terlalu berfokus pada evaluasi, maka secara tidak langsung siswa dilatih untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Alih-alih menjadi pembelajar yang ingin tahu dan kritis, banyak siswa tumbuh sebagai pelaku strategi: bagaimana mendapatkan nilai tinggi dengan usaha minimal, bagaimana menebak pola soal, atau bagaimana menyenangkan guru.
Proses belajar pun menjadi kehilangan maknanya. Belajar tidak lagi dipandang sebagai proses internalisasi pengetahuan dan pengalaman, tapi sebagai jalan menuju angka tinggi. Ini sangat disayangkan, karena pendidikan seharusnya membuka potensi, bukan sekadar mengukur performa.
Apakah Pendidikan Kita Butuh Paradigma Baru?
Meskipun perubahan seperti penghapusan UN adalah langkah awal yang penting, namun perubahan paradigma adalah hal yang jauh lebih mendasar. Jika sistem masih menghargai nilai lebih daripada proses, maka perubahan nama ujian tidak akan membawa pengaruh besar. Pendidikan yang sejati seharusnya menghargai proses berpikir, keunikan individu, dan perjalanan pembelajaran, bukan hanya hasil akhir yang bisa diukur dalam bentuk angka.
Beberapa pendekatan pendidikan alternatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, portofolio, atau evaluasi deskriptif, mulai muncul di beberapa sekolah. Tapi untuk menjadi budaya nasional, dibutuhkan perubahan struktur, kebijakan, dan cara pandang dari semua pemangku kepentingan—dari pemerintah, sekolah, guru, hingga orang tua.
Kesimpulan
Meskipun Ujian Nasional telah dihapus, bayang-bayang penilaian masih kuat dalam sistem pendidikan kita. Evaluasi dengan wajah baru tetap membawa beban lama: tekanan angka, penilaian tunggal, dan pendekatan yang kurang memberi ruang pada keberagaman cara belajar. Transformasi pendidikan bukan hanya soal mengganti sistem penilaian, tapi juga membongkar paradigma bahwa nilai adalah satu-satunya ukuran sukses. Tanpa itu, pendidikan akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama, meski wajahnya berbeda.